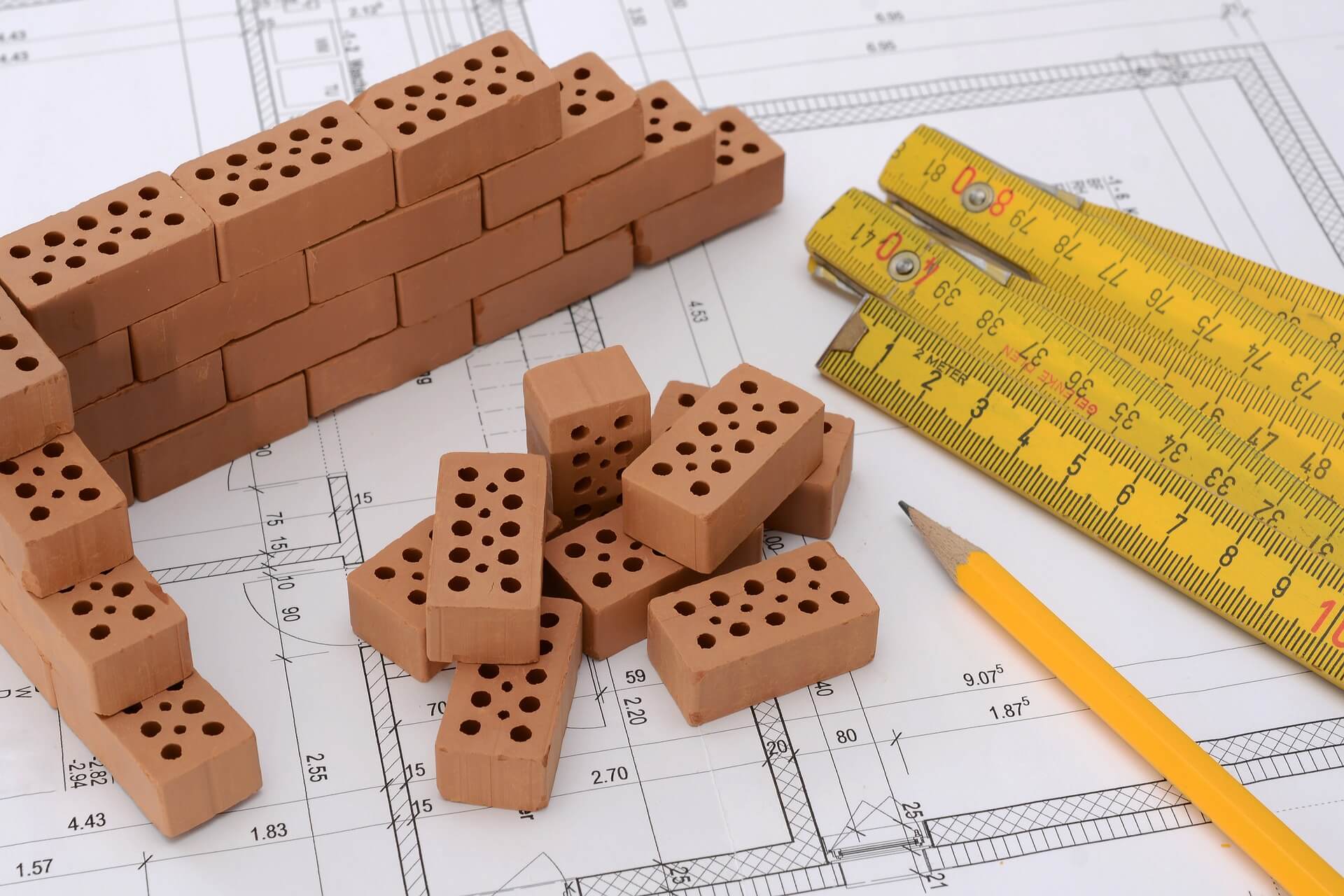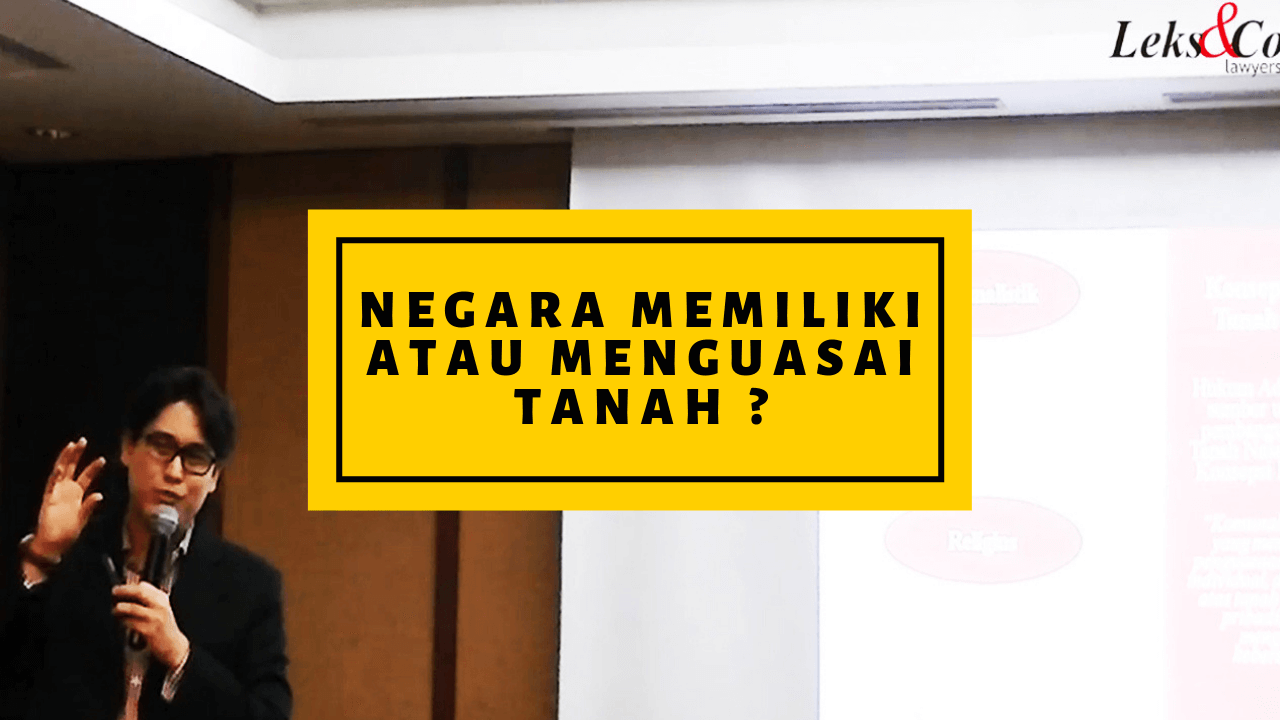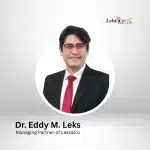Peraturan baru ini memberikan tiga bentuk pengakuan terhadap Tanah Ulayat, yaitu:
- Pencatatan dalam daftar tanah ulayat;
- Pendaftaran Tanah Ulayat sebagai hak pengelolaan; dan
- Pendaftaran sebagai hak milik bersama.
 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Adat atas Tanah di Indonesia
Prinsip-prinsip Dasar Hukum Adat atas Tanah di Indonesia
Hukum adat yang berkaitan dengan pertanahan bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Hukum adat telah berkembang dan tetap diterapkan di berbagai wilayah hingga kini. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”.
Dalam perspektif hukum adat, tanah memiliki kedudukan yang sangat fundamental bagi masyarakat adat. Tanah menjadi unsur pemersatu yang memperkuat ikatan dalam suatu persekutuan masyarakat hukum adat. Dalam hukum adat, hak penguasaan tanah yang tertinggi adalah hak ulayat. (Harsono, 2008: 184). Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan sepanjang masa (Harsono, 2008: 185-186).
Pengakuan hak ulayat tercantum dalam Pasal 3 dan Penjelasan Umum Bagian II Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) yang pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan negara atas tanah-tanah dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat tersebut masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Akan tetapi, pengakuan hak ulayat dalam UUD dan UUPA tampaknya masih belum cukup menjamin kepastian hukum atas hak ulayat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sengketa tanah berkenaan dengan hak ulayat. Permasalahan utama dari sengketa tanah ulayat adalah ketiadaan bukti kepemilikan hak atas tanah ulayat dari masyarakat adat.
Kerangka Regulasi Hak Tanah Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian ATR/BPN”) pada tahun 2015 mencoba mengatasi hal ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (“Permen ATR/BPN No. 9/2015”). Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 9/2015, masyarakat adat atau masyarkat yang berada dalam kawasan tertentu dapat memiliki hak milik bersama atas suatu tanah dengan diterbitkannya sertipikat Hak Komunal. Namun kemudian, Permen ini dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (“Permen ATR/BPN No. 18/2019”). Permen ATR/BPN No. 18/2019 ini mengatur mengenai penatausahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berujung dimana tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat hanya dicatat dalam daftar tanah, tidak seperti Permen ATR/BPN No. 9/2015 yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk mendapatkan hak komunal. Permen ATR/BPN No. 18/2019 ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (“Permen ATR/BPN No. 14/2024”).
“Berbeda dari regulasi sebelumnya, Permen ATR/BPN No. 14/2024 membuka jalan bagi tanah ulayat untuk tidak hanya dicatat dalam daftar tanah, tetapi juga diadministrasikan dan didaftarkan sebagai hak pengelolaan atau hak milik.”
Secara umum, Permen ATR/BPN No. 14/2024 merupakan langkah strategis dari Pemerintah untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia. Berbeda dengan Permen ATR/BPN No. 18/2019 yang hanya berujung pada tanah ulayat dicatatkan dalam daftar tanah, Permen ATR/BPN No. 14/2024 mengatur secara komprehensif mulai dari pengadministrasian pertanahan hak ulayat sampai dengan pendaftaran tanah hak ulayat yang dapat menjadi hak pengelolaan atau hak milik.

Karakteristik Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen ATR/BPN No. 14/2024 mengatur bahwa hak ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat dinyatakan masih ada apabila:
- terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari; dan/atau
- terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warganya.
Pasal 2 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 14/2024 mengatur bahwa masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Karakteristik masyarakat hukum adat dibedakan dalam:
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; atau
- Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat.
“Perbedaan antara kedua masyarakat hukum adat tidak mudah dipahami”
Berdasarkan Pasal 1 Permen ATR/BPN No. 14/2024, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat. Sedangkan, Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/ atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku.
Akan tetapi, pembagian masyarakat hukum adat tersebut tidak mudah dipahami karena peraturan ini tidak menyertakan contoh yang dapat dijadikan acuan untuk membedakan keduanya. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang dapat kita lihat. Pertama, terdapat penekanan yang berbeda dalam definisi kedua masyarakat adat tersebut. Definisi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mencakup harta benda dan harta kekayaan yang dimiliki bersama serta sistem nilai yang menentukan tatanan adat dan aturan-aturan adat, sementara tidak disebutkan harta benda dan harta kekayaan dalam Kelompok Masyarakat Hukum Adat. Penekanan pada Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat ini lebih kepada perhimpunan sebagai satu satuan sosial dan berdasarkan kepentingan bersama meskipun keduanya tetap mengacu pada hukum adat. Melihat pada pengaturan sebelumnya dalam Permen ATR/BPN No. 9/2015, Permen ATR/BPN membedakan masyarakat hukum adat dengan masyarakat dalam kawasan tertentu sebagai penerima hak komunal. Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 9/2015 menjelaskan persyaratan masyarakat hukum adat meliputi:
- masyarakat berbentuk paguyuban,
- ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya,
- ada wilayah hukum adat yang jelas dan
- ada pranata dan perangkat hukum yang masih di taati. Sedangkan, Pasal 3 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 9/2015 menjelaskan bahwa syarat masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu yang dapat memiliki hak komunal antara lain:
- menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut,
- masih mengadakan pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Permen ATR/BPN No.14/2024 memang tidak lagi menggunakan istilah masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, namun dari pengertian dan syarat yang ada, terlihat bahwa Kelompok Anggota Masyarakat Adat memiliki konsep yang sama dengan istilah masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dalam Permen ATR/BPN No. 9/2015 yang lebih menekankan pada kepentingan bersama sekelompok orang pada suatu kawasan.
Kedua, kedudukan hukum antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat. Suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus mendapatkan penetapan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“Permendagri No. 52/2014”). Pasal 6 ayat (2) Permendagri No. 52/2014 mengatur bahwa bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan keputusan kepala daerah. Sedangkan, Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat hanya membutuhkan rekomendasi pemerintah daerah. Perbedaan bentuk pengakuan dan perlindungan ini jelas mempengaruhi kedudukan hukum kedua bentuk masyarakat hukum adat. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki kedudukan hukum lebih kuat. Sebagai contoh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, suatu hutan adat hanya dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melaui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah.
“Yurisprudensi Mahkamah Agung mengatur bahwa masyarakat hukum adat memerlukan pengakuan secara hukum”
Selain peraturan perundang-undangan, contoh konkrit dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/TUN/2016. Judex Facti Banding dalam pertimbangannya pada pokoknya menimbang bahwa masyarakat hukum adat harus benar-benar diakui dan tidak dapat diakui secara sepihak, tetapi memerlukan adanya suatu pengakuan secara hukum. Oleh karena tidak ada pengakuan secara hukum, maka Judex Facti Banding mempertimbangkan bahwa para penggugat sebagai masyarakat hukum adat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena para penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan oleh adanya objek sengketa berupa izin pemanfaatan kayu. Pertimbangan ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya masyarakat hukum adat yang dirugikan kepentingannya karena dalil para penggugat sebagai masyarakat hukum adat hanyalah pernyataan sepihak yang perlu pengakuan secara hukum melalui Peraturan daerah. Selain itu, dalam Permen ATR/BPN No.14/2024 juga secara jelas mengatur bahwa bidang tanah ulayat milik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki status sebagai tanah ulayat, meskipun permohonan hak pengelolaan tidak diajukan.
Ketiga, eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai pemegang hak pengelolaan telah diakui terlebih dahulu berdasarkan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”). Pasal 5 jo. Pasal 10 PP No. 18/2021 mengatur bahwa hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 18/2021 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat hukum adat yang menguasai Tanah Ulayat, telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat, pranata, atau perangkat hukum yang masih ditaati. Sedangkan, pemberian hak milik kepada Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu norma baru yang belum pernah diatur. Hal ini juga akan kami jelaskan pada bagian selanjutnya mengenai pendaftaran tanah.

Tanah Yang Tidak Dapat Dilakukan Pelaksanaan Hak Ulayat
Pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat tidak dapat dilakukan dalam hal bidang tanah:
- sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;
- merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial;
- merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan/atau
- tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh Ketentuan Konversi dalam UUPA.
Tahapan Pengadministrasian Tanah Ulayat
Pengadministrasian pertanahan hak ulayat dilakukan untuk mencatat tanah ulayat dalam daftar tanah ulayat melalui beberapa tahap sebagai berikut:
Inventarisasi dan Identifikasi
Inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dilaksanakan oleh direktorat jendral yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah yang dapat dibantu oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan/atau Lembaga adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat hukum adat juga dapat mengajukan permohonan inventarisasi dan identifikasi atas tanah ulayatnya. Inventarisasi hak ulayat dilakukan melalui survei keberadaan masyarakat hukum adat untuk mengumpulkan data mengenai:
- subjek dan karakteristik masyarakat hukum adat;
- tanah ulayat masyarakat hukum adat;
- hubungan bukum masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat;
- penetapan keberadaan masyarakat hukum adat; dan/atau
- data dan informasi lainnya.
Hasil kegiatan inventarisasi ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan identifikasi untuk mengetahui indikasi keberadaan tanah ulayat. Identifikasi dilakukan melalui penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat hukum adat dan memastikan tanah ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/atau perkara. Hasil inventarisasi dan hasil identifikasi disampaikan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan verifikasi melalui pengecekan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan.
Pengukuran dan Pemetaan
Berdasarkan hasil verifikasi, dilakukan pemasangan tanda batas. Pemasangan tanda batas dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan dituangkan dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas.
Pemasangan tanda batas ditindaklanjuti dengan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat kepada kepala Kantor Pertanahan. Setelah itu, Kepala Kantor Pertanahan melakukan telaah spasial untuk memastikan bidang tanah ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, dan/atau tidak terdapat beban-beban lain; dan jelas letak, luas, atau batasnya, untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat.
Berdasarkan hasil telaah spasial, direktur jenderal yang membidangi survei dan pemetaan memerintahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan sesuai letak tanah ulayat untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sesuai dengan luasan kewenangan pengukuran guna mendapatkan data fisik tanah ulayat.
“Permen ATR/BPN No. 14/2024 menghadirkan terobosan: tanah ulayat kini dapat dicatat tanpa harus menunggu penetapan masyarakat hukum adat terlebih dahulu.”
Pencatatan Daftar Tanah Ulayat
Bidang tanah ulayat yang sudah diukur dan dipetakan serta dibubuhkan nomor identifikasi bidang tanah pada peta pendaftaran, dicatat dalam daftar tanah ulayat pada Kantor Pertanahan sesuai letak tanah dan Kantor Pertanahan akan menerbitkan salinan daftar tanah ulayat yang kemudian disampaikan kepada masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah.
Proses pencatatan tanah ulayat ke dalam daftar tanah ulayat dalam Permen ATR/BPN No. 14/2024 ini berbeda dengan pengaturan Permen ATR/BPN No. 18/2019. Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 18/2019 mensyaratkan bahwa sebelum dilakukan proses penatausahaan tanah ulayat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat wajib terlebih dahulu mendapatkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Permen ATR/BPN No. 14/2024 ini memberikan terobosan bahwa proses pengadministrasian tanah ulayat sampai dengan proses pencatatan tanah ulayat ke daftar tanah ulayat dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu. Sebaliknya, salinan daftar tanah ulayat yang diberikan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat. Akan tetapi, dalam hal masyarakat hukum adat ingin mengajukan pendaftaran tanah ulayat, khususnya untuk hak pengelolaan, maka penetapan masyarakat hukum adat menjadi syarat pendaftaran tanah ulayat untuk hak pengelolaan.

Pendaftaran Tanah Ulayat
Hak Pengelolaan
Sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian umum, pemberian hak pengelolaan terhadap tanah ulayat ini telah diatur dalam PP No. 18/2021. Penjelasan Pasal 4 PP No. 18/2021 mengatur bahwa penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarkat hukum adat. Pemberian hak pengelolaan kepada masyarkat hukum adat ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Permen ATR/BPN No. 14/2024.
Pasal 15 Permen ATR/BPN No. 14/2024 mengatur bahwa bidang tanah ulayat yang sudah dicatat dalam daftar tanah ulayat dapat diajukan permohonan hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri melalui Kantor Pertanahan. Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan memuat keterangan mengenai:
- bidang tanah ulayat yang akan didaftarkan;
- subjek hukum kesatuan masyarakat hukum adat;
- hubungan hukum antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat;
- penetapan keberadaan masyarakat hukum adat.
“Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan dapat diajukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan.”
Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan dilengkapi dengan:
- Identitas:
- Pemohon; atau
- Pemohon dan kuasanya, (apabila dikuasakan);
- Peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur, atau peraturan/keputusan bupati/wali kota yang menetapkan masyarakat hukum adat;
- Peta bidang tanah;
- Dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- Bukti perpajakan yang berikaitan dengan tanah yang dimohon (apabila ada;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang memuat:
- Informasi mengenai bidang tanah ulayat;
- Sejarah penguasaan dan kepemilikan bidang tanah ulayat;
- Hubungan hukum antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat;
- Pernyataan bidang tanah ulayat tidak sedang dalam sengketa; dan
- Informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat.
Berdasarkan syarat-syarat di atas, terlihat bahwa permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dari bahwa peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur, atau peraturan/keputusan bupati/wali kota yang menetapkan masyarakat hukum adat menjadi salah satu kelengkapan untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah berupa hak pengelolaan.
“Tanah ulayat tetap diakui sebagai tanah ulayat meskipun tidak didaftarkan sebagai hak pengelolaan”
Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk keperluan pemeriksaan tanah, pemohon atau kausanya mengumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan/atau keterangan yang bersangkutan.
Menteri berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan penetapan hak pengelolaan atas tanah ulayat berdasarkan usulan kepala kantor pertanahan. Keputusan yang mengabulkan penetapan hak pengelolaan akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan akan dilakukan pencatatan dalam buku tanah dan penerbitan sertipikat hak pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penting untuk dicatat, Pasal 16 Permen ATR/BPN No. 14/2024 mengatur bahwa bidang tanah ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai hak pengelolaan oleh kesatuan masyarakat hukum adat tetap memiliki status tanah ulayat. Terhadap tanah ulayat yang tidak didaftarkan hak pengelolaan, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian.

“Pendaftaran hak milik atas tanah ulayat tidak memerlukan penetapan, melainkan cukup dengan rekomendasi pemerintah daerah dan silsilah yang mencerminkan ikatan asal-usul serta hubungan hukum antar anggota kelompok sesuai hukum adat yang berlaku.”
Read also: Differences of Right of Management under the Old and New Law
Hak Milik
Sebagaimana telah kami uraikan pada bagian umum di atas, pemberian hak milik kepada masyarakat adat pernah diatur dalam Permen ATR/BPN No. 9/2015 yang kemudian permen tersebut dicabut oleh Permen ATR/BPN No. Permen ATR/BPN No. 18/2019 yang hanya mengatur bahwa tanah ulayat didaftarkan dalam daftar tanah. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah ulayat juga tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”) atau pun PP No. 18/2021. Pasal 31 ayat (4) PP Pendaftaran Tanah hanya mengatur bahwa hak atas tanah memang dimungkinkan menjadi kepunyaan bersama beberapa orang. Namun, PP Pendaftaran Tanah dan PP No. 18/2021 tidak mengatur mengenai pemberian hak milik atas tanah ulayat kepada masyarakat adat.
Permen No. 14/2024 kemudian mengatur ketentuan baru bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dapat ditetapkan menjadi hak milik atas nama Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat sebagai tanah bersama. Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik diajukan oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat kepada kepala Kantor Pertanahan.
Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik memuat keterangan mengenai:
- bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan;
- subjek hukum Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah; dan
- hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat.
Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik dilengkapi dengan:
- identitas:
- Pemohon; atau
- Pemohon dan kuasanya (apabila dikuasakan);
- Peta bidang tanah;
- Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, (apabila ada);
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang memuat:
- Informasi mengenai bidang tanah ulayat;
- Sejarah penguasaan dan kepemilikan bidang tanah ulayat;
- Hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat;
- Pernyataan tidak sedang dalam sengketa; dan
- Informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat.
- Silsilah atau yang disebut dengan nama lain yang menginformasikan nama-nama anggota kelompok dan/atau hubungan hukum antar anggota kelompok sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku.
Permohonan pendaftaran hak ulayat berupa hak milik ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian data yuridis. Untuk keperluan penelitian data yuridis, pemohon atau kuasanya mengumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan/atau keterangan yang bersangkutan.
Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah juga peta bidang tanah diumumkan di Kantor Pertanahan dan kantor desa/kelurahan selama 30 (tiga puluh) hari kalender. Setelah 30 (tiga puluh) hari, daftar data yuridis dan data fisik disahkan oleh kepala kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis.
Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, dicatatkan penetapan hak milik atas tanah ulayat yang disahkan oleh kepala kantor Pertanahan. Penetapan hak milik atas tanah ulayat tersebut kemudian dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat hak milik.
Sertipikat Hak Milik Tanah Ulayat
“Nama pimpinan kelompok akan dicantumkan dalam sertipikat”
Sertipikat hak milik tanah ulayat mencantumkan nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat yang merupakan hasil kesepakatan tertulis dari Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat yang tercantum dalam sertipikat hak milik dilengkapi dengan menyebut kedudukan sesuai dengan hukum adatnya.
Berdasarkan prosedur di atas, terlihat bahwa Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat memerlukan rekomendasi pemerintah daerah sebelum mendaftarkan tanah ulayatnya menjadi hak milik. Namun, berbeda dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat tidak memerlukan penetapan berupa peraturan/keputusan daerah untuk mendapatkan hak atas tanah.

Kesimpulan
Permen ATR/BPN No. 14/2024 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi tanah ulayat masyarakat adat. Secara umum, terdapat tiga bentuk pengakuan tanah hak ulayat berdasarkan Permen ATR/BPN No. 14/2024, yakni:
- pencatatan tanah ulayat ke dalam daftar tanah ulayat,
- pendaftaran tanah ulayat melalui penerbitan hak pengelolaan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan
- pemberian status hak milik bersama bagi Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang mereka kuasai. Hal positif dari penerbitan Permen ini adalah adanya fleksibilitas dalam pengadministrasian tanah ulayat, di mana proses tersebut tidak wajib didahului oleh penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, kecuali apabila akan dilanjutkan dengan penerbitan hak pengelolaan dari tanah ulayat tersebut. Bahkan, hasil dari proses pengadministrasian ini justru dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui produk hukum daerah. Selain itu, peraturan ini menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi tanah ulayat, meskipun tetap memberi ruang bagi masyarakat hukum adat untuk mengajukan permohonan pengakuan secara aktif.
Pembagian antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dalam Permen ATR/BPN No. 14/2024 tidak mudah dipahami karena Permen ATR/BPN No. 14/2024 tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan kedua jenis masyarakat adat tersebut.Namun, terdapat beberapa perbedaan yang dapat kita lihat, yaitu:
- definisi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menekankan keberadaan harta kekayaan bersama serta sistem nilai dan aturan adat, sementara Kelompok Anggota lebih menitikberatkan pada perhimpunan sosial berbasis kepentingan bersama,
- dari segi kedudukan hukum, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus ditetapkan melalui keputusan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 52/2014, sementara Kelompok Anggota hanya memerlukan rekomendasi pemerintah daerah, sehingga posisi hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat lebih kuat. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti UU Kehutanan dan Permen LHK No. 9/2021,
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah diakui sebagai pemegang hak pengelolaan tanah ulayat dalam PP No. 18/2021, sedangkan pemberian hak milik kepada Kelompok Anggota merupakan norma baru yang belum pernah diatur sebelumnya.
Fitri Nabilla Aulia
Sources:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Jakarta:Djambatan.